Rencana Penulisan Buku Arsitektur
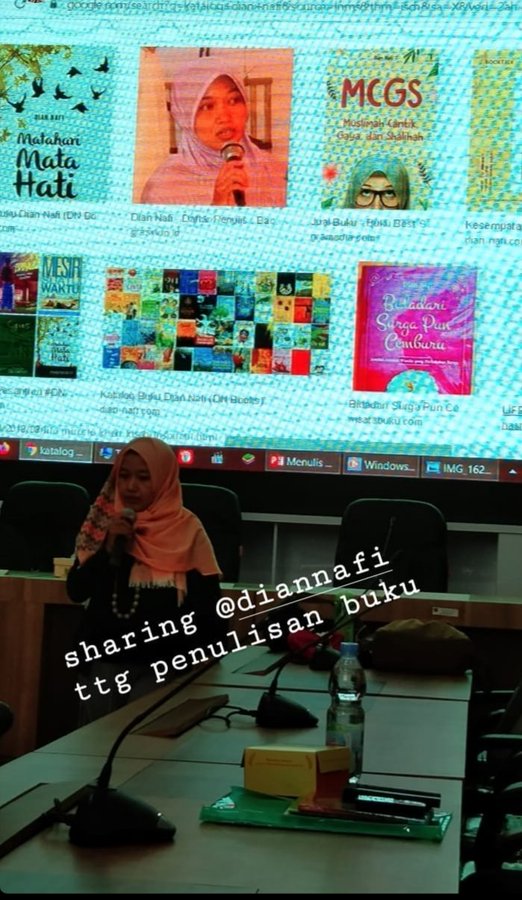
Insya Allah ada 16 kontributor ahli yang terdiri para dosen, doktor, profesor yang akan menulis bersama bunga rampai arsitektur ini.
Berikut salah satu tulisannya.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
What's next
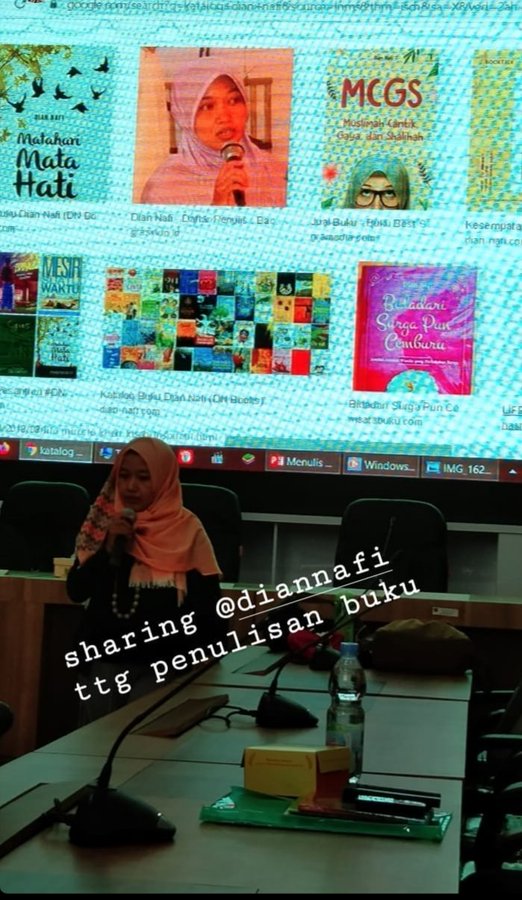
Insya Allah ada 16 kontributor ahli yang terdiri para dosen, doktor, profesor yang akan menulis bersama bunga rampai arsitektur ini.
Berikut salah satu tulisannya.
Lawang
Yang Hilang
Oleh Dian Nafi
Ada yang hilang siang itu saat kami datang.
Ia iconic. Menjadi menarik karena warna merahnya yang
dominan, bentuk kepala naga melintang dengan gigi-gigi menakutkan bagi
anak-anak yang memperhatikannya, setidaknya aku waktu kecil dulu. Cerukan,
tonjolan, lengkungan yang terbentuk oleh ukiran, paduan sulur-sulur stilisasi tumbuhan ala jawa dan nusantara yang kaya, bokor jambangan ala gujarat india dan
hindu budha, mahkota ala majapahit, kepala naga ala china.
Bersama-sama dengan ciri khas atap tajug tumpang tiga sebagai
adaptasi meru hindu, piring campa, gentong khong cina, tiang majapahit, lawang
bledheg menjadi simbol inkulturasi. Suatu upaya strategi walisongo dan Raden
Fatah dalam memadupadankan berbagai unsur di sekitarnya, menyatukan berbagai
perbedaan. Wujud adaptasi dan toleransi. Spiritnya mungkin bisa ditiru arsitek
mana saja untuk tujuan serupa. Entah itu apa bentuk dan interpretasinya.
Saat
aku akhirnya bisa melihat lagi versi asli lawang bledhegnya di museum Masjid
Agung Demak, tiba-tiba justru melintas dalam kepalaku Quran surat Ali imran ayat 133-136 yang menerangkan sifat
orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka yang segera bertobat, menyesali dosa,
balasannya adalah terampuni dan masuk surga. PINTU itu, pintu bledheg itu, pintu menuju sorga.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
Terjemah Surat Ali Imran Ayat 133-136:
133. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan
mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi
orang-orang yang bertakwa,
134. (yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang
maupun sempit[1], dan orang-orang yang menahan amarahnya[2] dan mema'afkan
(kesalahan) orang lain[3]. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan[4].
135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri[5], segera mengingat Allah[6], lalu
memohon ampunan atas dosa-dosanya[7], dan siapa lagi yang dapat mengampuni
dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu,
sedang mereka mengetahui.
136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.
Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.
Mahkota
itu gambaran dari orang-orang yang berinfak,
baik di waktu lapang maupun sempit. Kepala
naga atau apapun makhluk bergigi runcing itu adalah gambaran dari
orang-orang yang menahan amarahnya. Jambangan
adalah gambaran dari mema'afkan (kesalahan) orang lain. Dan sulur-sulur dedaunan itu gambaran dari
orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon
ampunan atas dosa-dosanya.
Adakah interpretasi ini mengada-ada? Mungkin iya. Tapi itulah
yang terlintas dalam benakku saat raga dan rasaku bersinggungan dengan raga dan
rasa pintu bledheg itu. Wallahu a’lam bishshowab.
Ornamen dan detail, bagaimanapun, adalah salah satu komponen
pembentuk arsitektur yang signifikan. Seperti halnya dalam cerita. Kita
mendapatkan kedalaman, nuansa, tone, warna, aura, ambience, kesan tertentu. Pintu
bledheg ini dengan segala ornamen dan detailnya adalah bagian dari Masterpiece.
Kenapa bukan kaligrafi? Bukankah ini masjid? Inilah kekuatan
kurator dan kreatornya. Sunan Kalijogo diamini Wali Songo dan Raden Fatah,
orang-orang di balik masterpiece ini tentu saja geng kuratornya. Kreatornya, Ki
Ageng Selo. Tapi ini versi rekaanku tentu saja. Sedangkan versi lainnya ada
banyak sekali.
Cerita rakyat Lawang Bledeg mengisahkan pemberontakan yang
dilakukan oleh Ki Ageng Selo kepada Sultan Trenggana, sebab sebagai keturunan
asli Prabu Brawijaya walaupun tidak diakui, Ki Ageng Selo merasa berhak atas
tahta Demak. Sunan Kalijaga tidak menggunakan kekerasan untuk melawan Ki Ageng
Selo, melainkan menggunakan jalur diplomasi. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa
esok yang akan menjadi raja Demak bukanlah Ki Ageng, melainkan keturunannya maupun
orang yang sangat dekat dengannya, jika Sunan Kalijaga berbohong, maka
keturunannya akan hidup sengsara. Ki Ageng Selo pun takluk dan diampuni oleh
Sultan Trenggana. Lalu Ki Ageng Selo membuat pintu bledheg dengan cara
menangkap petir kemudian dibuatnya sebuah pintu dan dipersembahkan sebagai
permintaan maaf.
Versi
lainnya, dalam tradisi lisan di beberapa daerah di Jawa Tengah, Ki Ageng Selo
merupakan tokoh yang terkenal bisa menangkap petir. Diceritakan, suatu hari Ki
Ageng Selo sedang mencangkul di sawah. Langit mendung lalu turun hujan dan
tiba-tiba petir menyambarnya. Namun, dengan kesaktiannya, dia berhasil
menangkap petir itu. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikatnya ke
sebuah pohon Gandrik.
Ketika
dibawa kepada Sultan Demak, naga tersebut berubah menjadi seorang kakek. Kakek
itu kemudian dikerangkeng oleh Sultan dan menjadi tontonan di alun-alun.
Kemudian datanglah seorang nenek mendekat, lalu menyiram air dari sebuah kendhi ke
arah kakek tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara petir menggelegar dan kakek
nenek tersebut menghilang.
Dari kisah tersebut
berkembang mitos kalimat, “Gandrik, aku iki putune Ki Ageng Selo” yang
artinya, “Gandrik, saya ini cucunya Ki Ageng Selo.” Kalimat itu, bagi sebagian
penduduk daerah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu misalnya, dipercaya dapat
menghindarkan mereka dari sambaran petir ketika hujan datang. Sigit Prawoto,
dosen Antropologi Sosial dan Etnologi Universitas Brawijaya, dalam bukunya Hegemoni
Wacana Politik menyebut, “pernyataan klaim kekeluargaan ini
mengandung keyakinan kultural bahwa seseorang yang berasal dari keturunan orang
yang memiliki kualitas (kasekten) tertentu akan mewarisi kualitas
tersebut.”
Kisah Ki Ageng Selo
menangkap petir diabadikan dalam ukiran pada Lawang Bledheg atau
pintu petir di Masjid Agung Demak. Ukiran pada daun pintu itu
memperlihatkan motif tumbuh-tumbuhan, suluran (lung), jambangan, mahkota
mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api.
Menurut Soetardi dalam Pepali
Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo merupakan keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit,
dari istrinya yang paling muda yang berasal dari Wandan atau Bandan atau Pulau
Banda Neira.
Dalam kitab Babad Tanah Jawi disebutkan, Ki Ageng Selo adalah
keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri
Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang
menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub, menurunkan Ki Ageng Getas
Pendawa. Dari Ki Ageng Getas Pendawa lahirlah Bogus Sogom alias Syekh
Abdurrahman alias Ki Ageng Selo.
Hidup di masa
kekuasaan Sultan Trenggana, awal abad ke-16, Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota
Prajurit Tamtama Pasukan Penggempur Kerajaan Demak. Sebab dalam ujian
mengalahkan banteng, dia memalingkan kepala saat melihat darah yang menyembur
dari kepala banteng setelah pukulannya kena mata sang musuh. Karena memalingkan
kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak
memenuhi syarat.
Penolakan itu
membuat Ki Ageng Selo berkeinginan mendirikan kerajaan sendiri. Bila cita-cita
ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannyalah
yang akan mencapainya.
Ki Ageng Selo
kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten
Purwodadi. Dia hidup sebagai petani dan memperdalam ilmu agama, filsafat serta
ilmu untuk memperluas pengaruh kepada rakyat.
Riwayat Ki Ageng
Selo juga menyebut kalau beliau mempunyai putra bernama Ki Ageng Enis, yang
selanjutnya mempunyai putra bernama Ki Ageng Pamanahan. Cucu Ki Ageng Selo ini
menikah dengan putri sulung Kiai Ageng Wanasaba, dan dianugerahi putera bernama
Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sultan Sutawijaya. Keinginan Ki Ageng Selo mendirikan kerajaan sendiri terwujud oleh
cicitnya ini. Sutawijaya merupakan pendiri Kerajaan Mataram kedua atau
Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada 1587-1601 M.
Sebelumnya, Ki Ageng Enis juga
sempat berguru pada Sunan Kalijaga—satu angkatan dengan muridnya yang
termasyhur yakni Jaka Tingkir. Ki Ageng Enis lalu diminta bertempat tinggal di
Dusun Lawiyan guna mengajarkan agama Islam. Maka dari itu, putra terakhir Ki
Ageng Selo ini akhirnya lebih dikenal sebagai Ki Ageng Lawiyan.
Itulah salah satu cerita yang
membuktikan betapa berpengaruhnya keturunan Ki Ageng Selo dalam persebaran
Islam di Pulau Jawa. Garis keturunan Ki Ageng Selo diakui sebagai cikal bakal
yang menurunkan raja atau pimpinan. Bukan hanya raja di Kesultanan Demak,
Pajang, Mataram, Yogyakarta, atau Surakarta, namun konon katanya, Abdurrahman
Wahid atau Gus Dur juga jadi salah seorang keturunan Ki Ageng Selo. Banyaknya
keturunan Ki Ageng Selo yang menjadi orang besar, membuktikan bahwa tirakat yang
beliau lakukan demi anak dan cucunya menjelma berkah bagi semesta alam.
Ki Ageng Selo menanamkan pengaruh kepada masyarakat lewat
syair yang ditulis sebagai Pepali. Pepali ini kemudian diwariskan kepada
keturunannya sebagai kitab yang berisikan didikan kesusilaan, kebatinan dan
keagamaan.
Aja
sira ngagungkeun akal. Wong akal ilang baguse. (Jangan kamu menyombongkan akalmu. Orang berakal hilang
bagusnya.) Itu adalah salah satu ajarannya.
Semasa hidup, beliau dikenal memiliki kemampuan menabuh
alat musik ganjur yang bisa menarik penduduk—dan di saat momen itulah Ki Ageng
Selo melakukan dakwah Islamnya. Selain itu, Ki Ageng Selo juga mendirikan
madrasah untuk mendidik masyarakat agar paham dan taat terhadap ajaran Islam.
Muridnya datang dari berbagai daerah dan macam-macam kalangan. Salah satunya Mas
Karebet—yang kelak menjadi Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya.
alat musik ganjur yang bisa menarik penduduk—dan di saat momen itulah Ki Ageng
Selo melakukan dakwah Islamnya. Selain itu, Ki Ageng Selo juga mendirikan
madrasah untuk mendidik masyarakat agar paham dan taat terhadap ajaran Islam.
Muridnya datang dari berbagai daerah dan macam-macam kalangan. Salah satunya Mas
Karebet—yang kelak menjadi Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya.
Filsafat hidup yang diajarkan Ki Ageng Selo merupakan
perpaduan dari unsur-unsur keagamaan Islam dan Hindu. Pengaruh yang disebarkan
sang filsuf ini mampu manjadikan desanya bernama Selo. Selow. Slow. Situs makam Ki Ageng Selo yang terletak di belakang
Masjid Ageng Selo kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah masih
ramai dikunjungi peziarah.
Ukiran bergambar naga yang berada di pintu Bledeg merupakan
perwujudan petir yang pernah dipersembahkan Ki Ageng Solo kepada Kerajaan Demak
pada zaman Sultan Trenggono. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa kesaktian Ki
Ageng Selo menangkap petir hanyalah kiasan alias metafora.
Versi lainnya mengatakan bahwa pintu bledheg itu menyimpan
rajah agar Demak tidak mudah diserang. Versi lainnya lagi menyampaikan pintu
bledheg menjadi daya tarik yang sengaja disebarkan kepada rakyat/masyarakat
kala itu, agar mereka pergi ke masjid Agung demi bisa melihat pintu ini. Ada
pula versi yang mengisahkan bahwa pintu ini simbol bahwa saat masuk ke dalam
masjid agung Demak, orang-orang harus melepaskan kebanggaan mahkotanya, menahan
emosi amarahnya, kekayaannya (yang biasanya disimpan dalam bokor jambangan) tak
lagi ada artinya.
Mau tahu versi lainnya lagi? Ada yang bilang Sultan Trenggono
agak salah strategi, karena justru menyuruh Ki Ageng Selo yang menangkap petir.
Sehingga justru keturunan ki Ageng Selo-lah yang kemudian menjadi raja-raja
yang berjaya di tanah Jawa.
What's next
Batik lawang bledheg dengan segala keindahan kreasinya, baik
pilihan dan muasal ornamen, perpaduan juga gradasi warna merah hijau emasnya,
legenda dan mitos yang membersamainya, serta tentu saja beribu interpretasinya
ini sangat potensial menjadi ciri khas demak.yang bisa dibawa ke kancah
internasional.
Nilai-nilai adaptif, inkulturasi, akulturasi, enkulturasi,
toleransi dari lawang bledheg semestinya menjadi inspirasi terus menerus demi
menjaga kebhinekaan di nusantara, bahkan menyatukan perbedaan dan keragaman di
seluruh dunia dan alam semesta.
Ingat film Gundala (2019)
garapan sutradara Joko Anwar yang tayang di bioskop beberapa waktu lalu?
Penciptaan Gundala oleh komikus Harya Suraminata disebut-sebut terinspirasi
oleh Ki Ageng Selo, tokoh legenda yang diceritakan bisa menangkap petir. Nama
Gundala sendiri berasal dari kata "gundolo" yang artinya petir.
Dan menakjubkan, bahwa film Gundala akhirnya diputar juga di kancah festival
internasional. So proud! Ki Ageng Selo memang maestro. Dan pintu bledheg
memanglah masterpiece.
Aku tak pernah bisa membayangkan seperti apakah masjid agung Demak
tanpa lawang bledeg. Tapi siang itu benar terasa ada yang hilang saat lawang
bledhegku tertutup backdrop acara sosialisasi pilkada di serambi masjid yang
akan berlangsung malamnya. Semoga bukan perlambang bahwa yang profan menutupi
yang sakral. Alangkah eloknya jika lawang bledheg justru tetap ditampilkan saat
ada acara-acara di serambi. Ia adalah ciri khas sekaligus sumber inspirasi.
Ialah pintu sorga.











